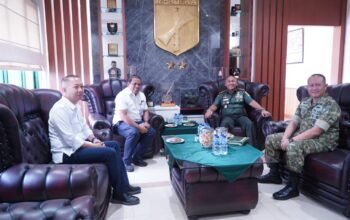Di ruang digital Indonesia, percakapan publik kian riuh. Namun, tidak seluruhnya lahir secara organik.
Dalam satu dekade terakhir, muncul dua aktor yang perannya semakin menentukan arah opini: buzzer dan clipper.
Keduanya bekerja di balik layar, menggerakkan narasi, membentuk persepsi, bahkan memelintir makna sering kali tanpa disadari publik.
Fenomena ini bukan lagi sekadar gosip warganet.
Sejumlah riset dan laporan media menunjukkan bahwa industri opini digital telah berkembang menjadi ekosistem tersendiri, dengan struktur kerja rapi, pembiayaan berjenjang, dan keterkaitan erat dengan kepentingan politik maupun ekonomi.
Dari Opini Personal ke Operasi Terkoordinasi
Buzzer pada mulanya dipahami sebagai akun pendukung yang menyuarakan pendapat pribadi.
Namun, praktik di lapangan menunjukkan pergeseran signifikan.
Buzzer kini bekerja secara terkoordinasi, menggunakan naskah seragam, waktu unggahan yang diatur, serta target narasi yang jelas: menaikkan citra satu pihak dan meruntuhkan pihak lain.
Sementara itu, clipper menjadi aktor baru yang tak kalah berpengaruh.
Mereka memotong video berdurasi panjang pidato, diskusi, ceramah menjadi cuplikan singkat berdurasi 30 hingga 60 detik.
Potongan ini kemudian diberi judul provokatif, subtitle selektif, dan disebar masif di TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Shorts.
Dalam banyak kasus, satu kalimat yang diambil di luar konteks dapat mengubah makna keseluruhan pernyataan. Di titik inilah clipper berperan bukan sekadar sebagai editor, melainkan pembingkai realitas.
Struktur Kerja yang Tertata
Berdasarkan penelusuran sejumlah laporan investigatif dan pengakuan mantan pelaku, kerja buzzer dan clipper mengikuti pola berlapis:
Di lapisan atas, terdapat pemesan aktor politik, kandidat, kelompok kepentingan, atau perusahaan.
Mereka tidak berhubungan langsung dengan buzzer lapangan, melainkan melalui vendor komunikasi digital atau koordinator jaringan.
Di lapisan tengah, koordinator bertugas menyusun narasi, menentukan sudut serang, serta mendistribusikan tugas ke ratusan bahkan ribuan akun.
Di lapisan bawah, buzzer dan clipper menerima instruksi teknis: apa yang harus diunggah, kapan, dan dengan gaya bahasa seperti apa.
Data dari sejumlah laporan media nasional menyebutkan, satu isu besar dapat melibatkan 500 hingga 3.000 akun dalam satu waktu, terutama menjelang momentum politik seperti pemilu atau pembahasan kebijakan strategis.
Bayaran Berjenjang: Dari Puluhan Ribu hingga Miliaran
Soal bayaran, nilainya sangat bervariasi. Buzzer pemula umumnya dibayar Rp50.000–Rp150.000 per unggahan, atau paket harian. Akun dengan pengikut lebih besar bisa memperoleh Rp5–20 juta per bulan. Ada juga yang dibayar per komentar 300-500 perak.
Untuk level koordinator dan vendor, nilainya melonjak tajam. Dalam beberapa proyek besar, kontrak komunikasi digital disebut mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, tergantung durasi dan target politiknya.
Clipper berada di spektrum yang mirip. Clip biasa bisa dibayar ratusan ribu rupiah, namun clip yang berhasil viral dan masuk agenda media arus utama sering mendapat bonus tambahan.
Yang menarik, tidak semua bayaran berbentuk uang tunai.
Relawan, Modal Sosial, dan Janji Imbalan
Di sinilah batas antara aktivisme dan industri mulai kabur.
Banyak jaringan buzzer bermula dari kelompok relawan politik. Awalnya bergerak dengan semangat sukarela, bermodal loyalitas dan idealisme.
Namun seiring waktu, kerja yang konsisten dan terstruktur membuka akses pada sumber daya.
Relawan yang efektif mengelola opini kerap mendapat kepercayaan lebih: akses ke elite, posisi strategis dalam tim kampanye, hingga peluang menduduki jabatan formal setelah kekuasaan terbentuk.
Pola ini membuat istilah “relawan” kehilangan makna murninya. Ia berubah menjadi kendaraan mobilisasi, dengan imbal balik yang tidak selalu tercatat secara transparan.
Dalam konteks ini, publik mencatat sejumlah tokoh relawan yang kemudian masuk ke lingkar kekuasaan.
Salah satu nama yang pernah menjadi sorotan adalah Immanuel Ebenezer, figur relawan yang sempat menduduki jabatan pemerintahan sebelum akhirnya dinonaktifkan akibat proses hukum.
Kasus tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara relawan, kekuasaan, dan jabatan bukan sekadar spekulasi warganet, melainkan realitas politik yang memiliki konsekuensi hukum dan etika.
Dampak pada Demokrasi dan Kepercayaan Publik
Keberadaan buzzer dan clipper yang bekerja tanpa transparansi menimbulkan dampak serius. Diskursus publik menjadi dangkal, emosional, dan penuh polarisasi.
Kritik substantif tenggelam oleh serangan personal. Fakta kalah cepat dari potongan video yang viral.
Survei literasi digital nasional juga menunjukkan bahwa hoaks dan disinformasi politik masih menjadi masalah utama, terutama di media sosial berbasis video pendek.
Ketika opini diproduksi massal dan dikemas seolah-olah suara rakyat, publik kehilangan kemampuan membedakan mana aspirasi autentik dan mana rekayasa.
Menata Ulang Ruang Digital
Fenomena ini menuntut lebih dari sekadar penertiban akun. Diperlukan transparansi pendanaan komunikasi politik, pengawasan platform yang konsisten, serta literasi publik yang kuat.
Tanpa itu, ruang digital akan terus menjadi ladang manipulasi tempat suara paling keras menang, bukan yang paling benar.
Dan di tengah hiruk pikuk buzzer dan clipper, demokrasi perlahan kehilangan substansinya: dialog yang jujur dan rasional.(AL)